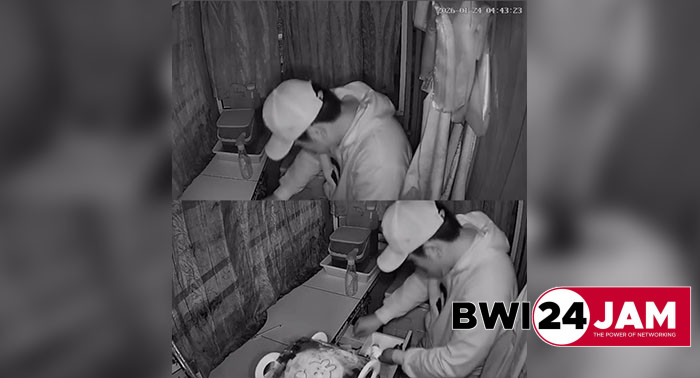Ilustrasi AI (Foto: BWI24Jam)
Ilustrasi AI (Foto: BWI24Jam)
BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Belakangan ini gema suara sound horeg tidak hanya meruntuhkan atap dan memecahkan kaca jendela rumah warga. Suara nyaring yang dihasilkan dari tumpukan sound system itu, ternyata tidak hanya menimbulkan keresahan dan penolakan sebagian besar masyarakat Jawa Timur, khususnya, tetapi juga mendorong para ulama untuk mengeluarkan fatwa yang berlandaskan dalil-dalil sahih. Sebuah fatwa haram itu kemudian menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat yang “gema”-nya seolah-olah menandingi suara sound horeg.
Fatwa pengharaman sound horeg itu diputuskan dalam Forum Satu Muharram (FSM) 1447 Hijriah di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan. Melansir NU Online Jatim, forum bahtsul masa’il yang diselenggarakan pada Kamis-Jum’at (26-27/6/2025) itu mengeluarkan fatwa tegas berkenaan dengan fenomena sound horeg yang selama empat tahun terakhir digandrungi masyarakat. KH. Muhibbul Aman Aly, pengasuh Pondok Besuk, menyatakan dengan tegas: keputusan tersebut (haram) bukan semata karena kebisingan suara, melainkan karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg itu sendiri.
Keputusan Pondok Besuk itu kemudian mendapatkan respons dari PBNU dan MUI Jawa Timur. Dilansir dari Inilah.com, kedua lembaga ini mendukung keputusan yang disampaikan Kiai Muhib tadi. Sehingga, secara bersamaan, mereka mendorong pemerintah untuk membuat aturan dan menertibkan sound horeg tersebut. Sementara Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengaku jika pihaknya sedang mencari solusi untuk mengatasi persoalan sound horeg yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Tentu fatwa itu tidak bersifat “absolut”. Keputusan hukum (Islam) terhadap fenomena sound horeg di kalangan ulama bisa beragam. Sebab fatwa itu nisbi, tidak absolut. Hanya saja, sesuai istinbath hukum yang diselenggarakan para ulama di Pondok Besuk, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, pelaksanaan sound horeg itu kemudian dihukumi haram. Bisa jadi, di forum yang lain, hukum sound horeg justru mubah, makruh, dan seterusnya.
Namun, ulasan ini tidak bermaksud mengulas fatwa itu. Sebab demikian bukan kapasitas saya. Baiknya kita serahkan persoalan itu kepada ahlinya. Terlepas dari fatwa “haram” Pondok Besuk itu, saya hendak membaca sound horeg dari sudut pandang lain: “sound horeg sebagai fenomena budaya”. Sehingga untuk membaca fenomena sound horeg itu, saya tidak menggunakan pendekatan hukum—sebagaimana yang dilakukan para kiai di Pondok Besuk, melainkan menggunakan pendekatan cultural studies (kajian budaya).
Menelisik Sejarah Sound Horeg di Jawa Timur
Beberapa tahun terakhir, parade battle sound system yang sering digelar di Jawa bagian timur menjadi buah bibir masyarakat. Beragam tanggapan kemudian muncul, khususnya di media sosial. Namun, sejauh ini, kemunculan istilah “sound horeg” itu masih cenderung kurang begitu dipahami masyarakat luas. Oleh karena itu, kita perlu menelisik istilah dan sejarah sound horeg ini.
Menurut Kamus Bahasa Jawa-Indonesia I (1993), kata “horeg” memiliki arti “getar” dan “berguncang”. Sementara kata “sound” lebih dekat dengan “audio”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ini berarti alat peraga yang bersifat dapat didengar. Sehingga sound horeg bisa dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan sistem audio (sound system) berukuran besar yang menghasilkan suara keras, dan suara itulah yang kemudian menyebabkan getaran atau guncangan di sekitar di mana sound horeg itu digelar. Umumnya, sound horeg kerap dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti karnaval (parade budaya), konser, dan dalam kegiatan yang bersifat kolektif lainnya.
Sejauh ini, kemunculan parade sound horeg ini belum ditemukan secara jelas. Kepastian kapan dan di mana fenomena sound horeg ini pertama kali muncul, sampai saat ini belum menemukan kejelasan. Namun, ada sebuah penelitian mengenai sound horeg di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, yang bisa kita jadikan rujukan. Penelitian itu dilakukan oleh Allysa Salsa Bilatul Kh, dkk dengan judul: “Perkembangan Sound System Sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi” (Jurnal Risoma, 2024).
Dalam artikel itu, sketsa sejarah kemunculan sound system di Banyuwangi diuraikan secara ringkas hingga menjadi sebuah “budaya”. Menurut Allysa, dkk (2024: 226), di Desa Sumbersewu, Banyuwangi, fenomena sound horeg sudah lama dilakukan masyarakat. Tren battle sound (adu suara sound) yang belakangan menjadi polemik itu ternyata pertama kali digelar di Desa Sumbersewu.
Secara historis, battle sound itu sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 1990-an hingga 2000-an, parade sound system di Banyuwangi mulai berkembang. Mulanya, sound system digunakan untuk perayaan takbiran (malam hari raya) masyarakat setempat. Namun, seiring bergulirnya waktu, tradisi “takbir keliling” yang menggunakan sound system itu semakin besar. Pada tahun 2005, sebagian masyarakat menyewa sound system dari luar kota, seperti Jember dan Malang, untuk memeriahkan malam takbiran yang diselenggarakan di lapangan.
Memang, di daerah lain, seperti Malang, Blitar, Kediri, dan Tulungagung sudah terkenal dengan karnaval sound system. Hanya saja, belum ada tradisi battle sound—yang mengadu antarsuara sound. Oleh karenanya, masyarakat Sumbersewu menyewa sound system dari luar kota untuk digunakan dalam memeriahkan malam takbiran tersebut. Bahkan, Allysa, dkk (2024: 227) mencatat, sejak tahun 2022, fenomena sound horeg di Sumbersewu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena masyarakat (pemuda) dari desa lain ikut memeriahkan di lapangan Sumbersewu. Dan mereka mulai menyewa sound system dari luar kota Jawa Timur hingga Jawa Tengah.
Fenomena battle sound atau sound horeg di Desa Sumbersewu ini bisa dianggap sebagai sebuah kesenian musik modern yang dikembangkan melalui bergam jenis lagu. Akan tetapi, belakangan, musik yang diputar ialah jenis disc jockey (DJ) dan remix. Karena musik semacam ini akan menghasilkan suara keras yang “menggelegar”.
Subkultur dalam Lanskap Cultural Studies
Kebudayaan, menurut Koentjaraningrat (1985), kebudayaan masyarakat itu luas. Tetapi kita dapat mengidentifikasi kebudayaan melalui apa yang disebut Koentjaraningrat sebagai “unsur-unsur kebudayaan yang universal”. Unsur-unsur tersebut meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan; sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; kesenian; sistem mata pencarian hidup; dan sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1985: 2). Dengan unsur universal ini, kita dapat mengetahui kebudayaan dalam komunitas masyarakat tertentu.
Kemudian, manifestasi dari kebudayaan tersebut setidaknya ada tiga: pertama, kumpulan ide-ide, hahasan, nilai, norma, peraturan, dan seterusnya; kedua, segenap aktivitas yang mempunyai pola dari manusia dalam masyarakat; ketiga, benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1985: 5). Ketiga wujud kebudayaan ini dapat kita temui dalam realitas kehidupan kita. Oleh karena itu, kita (manusia) disebut sebagai “manusia berkebudayaan”.
Dalam cultural studies, kebudayaan dibagi menjadi dua: budaya dominan dan sub-budaya (subkultur). Budaya dominan adalah jenis kebudayaan yang menguasai masyarakat, sedangkan sub-budaya (subkultur) adalah jenis kebudayaan yang berada di pinggiran (periferal). Kedua jenis kebudayaan ini, agar bisa tetap hidup di suatu komunitas tertentu, memiliki agen masing-masing (Hasan, 2011: 219). Misalnya, dalam kebudayaan masyarakat Jawa (dominan) terdapat “budaya-budaya” kecil yang terkadang berbeda dengan budaya Jawa yang dominan tersebut.
Keberadaan subkultur itu juga menjadi objek kajian budaya kontemporer. Secara definitif, dalam cultural studies, subkultur (subculture) dipahami sebagai sekelompok orang yang mempunyai budaya “berbeda” dengan kebudayaan yang dominan—sering dipraktikkan oleh masyarakat. Senada dengan hal ini, menurut Chirs Barker (2003), subkultur merupakan “seluruh cara hidup” dan “peta makna” yang berbeda dengan arus utama budaya masyarakat yang lebih besar (Barker, 2003: 378). Dengan demikian, subkultur adalah klasifikasi yang berusaha memetakan dunia sosial dalam tindakan representatif—yang berbeda, unik, dan khas.
Lebih jauh, subkultur juga didefinisikan sebagai gerakan subversif terhadap apa yang dianggap mapan. Gerakan perlawanan itu, menurut Dick Hebdige, dilakukan secara kolektif oleh komunitas tertentu untuk “menolak” kemapanan budaya (Hebdige, 1979: 148; Hasan, 2011: 221). Umumnya, definisi subkultur ini merujuk kepada gerakan-gerakan underground di kalangan anak muda. Karena mereka merasa termarginalisasi oleh budaya dominan yang represif.
Selanjutnya, eksistensi subkultur itu memiliki lima fungsi utama dalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Brake (dalam Barker, 2003: 379): pertama, menyediakan solusi atas berbagai masalah sosial-ekonomi dan struktural; kedua, menawarkan suatu bentuk identitas kolektif yang berbeda dari sekolah dan kerja; ketiga, memperoleh ruang bagi pengalaman dan gambaran alternatif realitas sosial; keempat, menyediakan beragam kegiatan hiburan yang bermakna sebagai pengganti sekolah dan kerja; kelima, memberikan solusi bagi dilema identitas eksistensial.
Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa di dalam komunitas masyarakat terdapat budaya yang dominan, suatu budaya yang ditopang oleh kekuasaan dan masyarakat secara bersama-sama. Namun, secara alamiah, setiap kekuasaan niscaya dihadapkan dengan “resistensi” atau perlawanan. Dalam konteks ini, kebudayaan yang dominan akan dihadapkan pada subkultur yang menjadi entitas subversif. Selain itu, subkultur juga mempunyai keunikan dan ciri khas yang berbeda dengan kebudayaan dominan tersebut. Bagaimanapun, baik budaya dominan atau subkultur, tidak mungkin dilepaskan dari peran “agen” (kumpulan individu).
Sound Horeg Sebagai Fenomena Budaya?
Seperti yang telah diulas sebelumnya, perspektif yang digunakan dalam membaca fenomena sound horeg di Jawa Timur ialah cultural studies, khususnya subkultur. Pada bagian ini, saya akan membaca sound horeg sebagai fenomena budaya di Indonesia secara umum, dan di Jawa bagian timur secara khusus. Maka pertanyaan yang hendak dijawab dalam subbab ini: apakah sound horeg termasuk ke dalam subkultur masyarakat?
Ketika menelisik kemunculan sound horeg atau juga dikenal battle sound di Banyuwangi, terutama di Desa Sumbersewu itu, kita dapat melihat bagaimana sebuah kelompok masyarakat mempunyai kreativitas yang kemudian menjadi tren di Provinsi Jawa Timur. Berangkat dari inisiasi masyarakat desa dalam memeriahkan malam takbiran, tak disangka tradisi modern itu kian menggema dan digandrungi masyarakat Jawa Timur, khususnya, selama beberapa tahun terakhir.
Kemudian dalam konteks “unsur universal” kebudayaan, fenomena sound horeg yang dilakukan masyarakat Jawa Timur (baik di Banyuwangi, Malang, Blitar, dan daerah-daerah lain) merupakan sebuah aktivitas “kesenian” serta “sistem teknologi dan peralatan”. Kesenian yang dibawa oleh sound horeg adalah kesenian musik modern. Sementara teknologi dan peralatan yang digunakan tidak lain adalah sound system itu sendiri. Selain itu, sound horeg juga dapat dianggap sebagai manifestasi kebudayaan, yaitu suatu aktivitas yang memiliki pola-pola tertentu dalam masyarakat.
Melalui battle sound (adu suara), para pengguna dan penikmat berposisi sebagai “agen budaya” (agent of culture) dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Lebih tepatnya, mereka berada di wilayah subkultur yang sering kali memperoleh stigma negatif dari masyarakat yang memegang teguh budaya dominan. Maka tak heran, jika kegiatan sound horeg ini banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat, dan “fatwa haram” dari para ulama Jawa Timur.
Adalah hal yang wajar, kalau sound horeg dicap sebagai kegiatan yang “amoral” dan berpotensi memicu seseorang untuk berbuat maksiat. Berbagai aspek, konteks, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan itu sampai detik ini juga masih ramai diperbincangkan. Namun, sejauh ini, pembahasan mengenai sound horeg lebih fokus pada dampak negatif yang ditimbulkan.
Misalnya, mengenai kebisingan suara hingga berbagai kerugian yang disebabkan oleh sound horeg sebagaimana yang telah dikaji oleh Ahmad Fauzi, dkk (2024); M. Khoirul Sahuri (2024); Sinta Della L. (2024); Aris Setiawan (2025); Ahmad Wildan Suhala, dkk (2025); dan Galieh Damayanti (2025). Padahal, kegiatan itu juga memiliki dampak positif, misalnya, dalam bidang ekonomi dan soio-kultural. Penelitian tentang hal ini telah dilakukan oleh Allysa Salsa Bilatul Kh, dkk (2024) dan M. Dzikri Darmawan & Riska Efendi (2024).
Terlepas dari dampak di atas, bagaimanapun, sound horeg adalah fenomena budaya (subkultur) masyarakat Jawa Timur. Ia memiliki pola dan keunikan tersendiri yang menjadi pembeda dari budaya dominan di Pulau Jawa bagian timur. Hanya saja, kita setengah hati menyebut sound horeg itu sebagai subkultur, karena acap kali kita masih terjebak ke dalam cara berpikir “generalisasi” dan seolah menutup mata mengenai sound horeg. Sebagai sebuah subkultur yang unik dan khas, upaya “memberantas” kegiatan battle sound atau sound horeg sama sekali tidak dibenarkan—dalam perspektif kebudayaan.
Alhasil, saya kemudian sepakat untuk mendorong pemerintah dalam membuat kebijakan khusus tentang sound horeg ini. Tentu kebijakan yang tidak “menekan” ekspresi para pencinta sound horeg. Pemerintah harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Sebab demikian berkaitan dengan orang banyak. Jika fenomena sound horeg terus dibentur-bentukan seperti sekarang ini, justru akan berpotensi memecah belah umat. Saya kira pemerintah perlu menggelar dialog interaktif antar-elemen masyarakat untuk membuat kebijakan khusus mengenai persoalan sound horeg ini dengan prinsips-prinsip demokratis.
Akhirul kalam, sesuai pembacaan yang telah dilakukan mengenai fenomena sound horeg yang belakangan menjadi “buah bibir” masyarakat, secara terbuka saya menyatakan: sound horeg adalah fenomena budaya (subkultur) kontemporer yang perlu dilestarikan dengan prinsip “tepa selira”. (*)
*Dendy Wahyu Anugrah, Cah Enom “Pinggiran” Banyuwangi


.png)